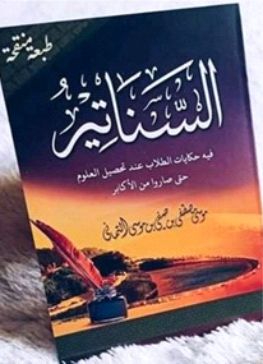Oleh: Taufiq Ahmad
Sebenarnya, saya sudah bisa mengkritik buku ini sejak melihat sampulnya. Tapi, demi menghargai idiom tradisional “don’t judge a book by its cover,” dan juga tulisan ini bukan dimaksudkan sebagai kurasi seni sampul buku, maka saya sempatkan untuk membacanya di tengah kesibukan ngopi. Dan ulasan ini adalah hasil bacaan saya yang tentu saja tidak sistematis alias keotik.
Secara ringkas, buku ini menjelaskan tentang lubang hitam dalam hukum pidana kita khususnya perihal relasi kuasa yang timpang sehingga menimbulkan korban perempuan dari yang paling ringan hingga hilangnya nyawa, yang dalam buku ini didefinisikan sebagai femisida. Femisida dibagi dalam dua kategori, langsung dan tidak langsung, yang pembedaan keduanya didasarkan pada niat pelaku (hal 13).
Konsepsi femisida yang mulanya diusung gerakan perempuan Amerika Latin yang kemudian diterapkan di berbagai negara, dibahas dalam buku ini khususnya negara Nikaragua, Guatemala, Meksiko, India, Spanyol, Nigeria, Malaysia, Belanda, Inggris, dan Turki (39-57) untuk mendapat gambaran perbandingan bagaimana negara-negara tersebut menangani persoalan ini.
Gambaran tersebut kemudian dipakai untuk menganalisis kondisi Indonesia dengan kendala ketiadaan istilah femisida, tapi itu bisa disiasati dengan kata kunci sepadan seperti pembunuhan terhadap istri, korban adalah istri, penganiayaan terhadap istri (hal 58). Beberapa temuan menunjukkan bahwa korban femisida tidak hanya dirampas nyawanya, melainkan juga mengalami penganiayaan berlapis dan sadis dari pelaku (hal 67).
Hukum pidana kita memang terlahir dari semangat modernisme yang terangkum dalam ethic of right, dan tentu saja belum beranjak pada ethic of care. Itulah yang membuat banyaknya korban perempuan yang keterkaitannya dengan relasi gender begitu saja dianggap sama dengan pembunuhan biasa.
Namun temuan Komnas Perempuan dalam buku ini menunjukkan adanya suatu fakta menonjol mengenai korban pembunuhan perempuan yang perlu disorot lebih jauh dari sekedar pembunuhan biasa. Buku ini menawarkan istilah khusus: femisida. Suatu istilah yang awalnya dipopulerkan oleh gerakan perempuan di Amerika Latin yang kini bentuk kongkritnya dilaksanakan di negara seperti Meksiko, Nikaragua, lalu meluber ke negara-negara lain di dunia, sebagaimana dikupas juga dalam buku ini.
Dan akhirnya, laiknya buku-buku yang memang ditujukan untuk merubah (sengaja pakai kata merubah, bukan mengubah) kebijakan, buku ini dipungkasi dengan rekomendasi kebijakan dalam berbagai aspek diantaranya aspek hukum, budaya, dsb.
Ada beberapa catatan yang sebenarnya tak terlalu berkaitan dengan perjuangan komnas perempuan dalam buku ini.
Pertama, kata femisida itu sendiri adalah kata-kata yang masih jarang dipakai di Indonesia. Waktu ulasan ini ditulis, saya coba googling hasilnya masih kurang dari 20.000 hasil. Jika googling itu saya persempit khusus hanya pada media massa, hasilnya lebih sedikit lagi yakni hanya 3000 temuan. Ini wajar sebenarnya mengingat bahkan KBBI (online) belum menyerapnya.
Hal itu berbeda dengan kata padanannya yang relatif banyak digunakan yakni “pembunuhan wanita” (>17,4 juta), atau “pembunuhan perempuan” (>13,4 juta). Begitu juga kata yang ada hubungannya dengan perjuangan perempuan seperti “feminisme” (>3 juta), “kesetaraan gender” (> 4 juta), “diskriminasi gender” (>1,7 juta), “kekerasan seksual” (> 10 juta), perjuangan perempuan (>15,9 juta) atau perempuan melawan (>20,5 juta—hore!).
Namun saya memprediksi bahwa kata femisida akan populer mengingat kita sudah punya relasi kata sejenis, seperti kata genosida (>700 ribu), atau kata-kata yang akrab dengan dunia saya seperti pestisida (>7,2 juta), fungisida (>2,2 juta) insektisida (>3,4 juta), herbisida (>2 juta) dan sida-sida lainnya. Artinya jika femisida menjadi makin umum, maka buku ini sudah berhasil mengkampanyekan kata femisida yang dianggap persoalan serius di negara ini.
Kedua, kampanye ethic of care ala Carol Gilligan yang kini banyak dipakai kalangan feminis itu, saya pikir akan mudah saja diterima dan diimplementasikan dalam bentuk perundang-undangan. Ini persis seperti begitu mudahnya negara kita meratifikasi berbagai aturan yang disahkan oleh PBB, seperti soal HAM yang bahkan masuk dalam UUD pada Agustus 2000, (10 Pasal dalam Bab XA, dari Pasal 28A-28J) dan dipertegas dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM. Atau juga ratifikasi soal pemanasan global dalam UU No 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to The UNFCCC. Yang artinya di atas kertas negara kita sebenarnya cukup progresif. Problem utamanya lagi-lagi adalah penegakannya yang seringkali jauh panggang dari api.
Selain itu, pangkal dari soal femisida jauh berakar dalam struktur sosial masyarakat Indonesia. Relasi yang timpang antar gender yang dianggap biang keladi femisida itu masih berdiri kokoh dengan topangan struktur ekonomi politik kita yang memang belum memihak perempuan. Dalam keluarga buruh misalnya, akan sulit jika dua-duanya bekerja sebab si anak akan terlantar, sementara itu daycare yang tersedia ongkosnya selangit, sehingga salah satunya terpaksa “mengalah” yang biasanya pihak perempuan. Mungkin saja pihak perempuan bisa ngotot, tapi tekanan kultural terkadang tak bisa dia tanggung.
Dan struktur ekopol yang tidak memihak perempuan itu ditambang dengan struktur sosial budaya. Model berislam yang menjadi agama mayoritas dari penduduk Indonesia, saya pikir turut berkontribusi dalam hal ini. Wacana pembongkaran dari sudut ini sudah banyak dilakukan kalangan liberal, tapi rupanya reaksi atasnya tak kalah kencang. Sebab bagaimanapun warisan keberislaman yang dominan saat ini adalah hasil tafsir model keberislaman seribu tahun silam atas ajaran Islam Nabi. Itu butuh kajian khusus.
Dan kalau mau lebih dalam lagi bongkar-bongkarannya, bisa ditelisik dari perspektif neurologis. Bisa dimulai dengan pembedaan otak masing-masing jenis kelamin atau gender, yang berevolusi sepanjang sejarah homo sapiens, dimana sejak 250 ribu tahun silam, perempuan lebih banyak berperan di ranah domestik sekitar goa, sementara para lelaki lebih banyak berburu. Itu terlihat dari perbedaan kemampuan navigasi yang kita lihat saat ini, dimana lelaki lebih lihai navigasi jarah jauh (misalnya baca peta) sementara perempuan lebih ekspert navigasi jarak dekat (misal tata letak barang-barang rumah tangga). Ini tentu berpengaruh pada relasi antar gender.
Kira-kira seperti itu. Langsung lompat pada pamungkasnya saja dari pada pusing, yaitu seandainya rekomendasi Komnas Perempuan memang diimplementasikan di negara kita, itu tentu merupakan suatu kemajuan yang sangat berarti. Tinggal bagaimana rekomendasi itu dilanjutkan pada suatu upaya meminimalisir penyebab dari kokohnya ketimpangan relasi kuasa antar gender itu, sebab urusannya bukan semata “kesadaran masyarakat” belaka. Relasi kuasa itu melibatkan struktur ekonomi politik, bahkan lebih jauh pada bentukan neuron manusia, yang juga harus ditangani secara lebih komprehensif.
Identitas Buku
Judul : Lenyap dalam Senyap: Korban Femisida dan Keluarganya Berhak atas Keadilan
Penulis : Rainy Maryke Hutabarat, dkk
Tebal : xvi + 116 halaman
Penerbit : Komnas Perempuan
Tahun : 2022
ISBN` : 9786023300822
Peresensi : Taufiq Ahmad