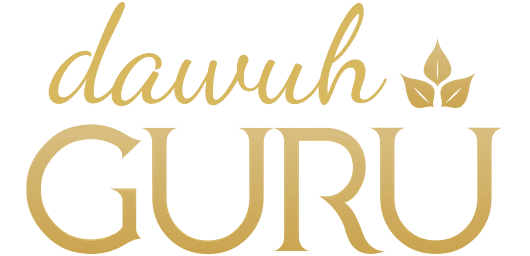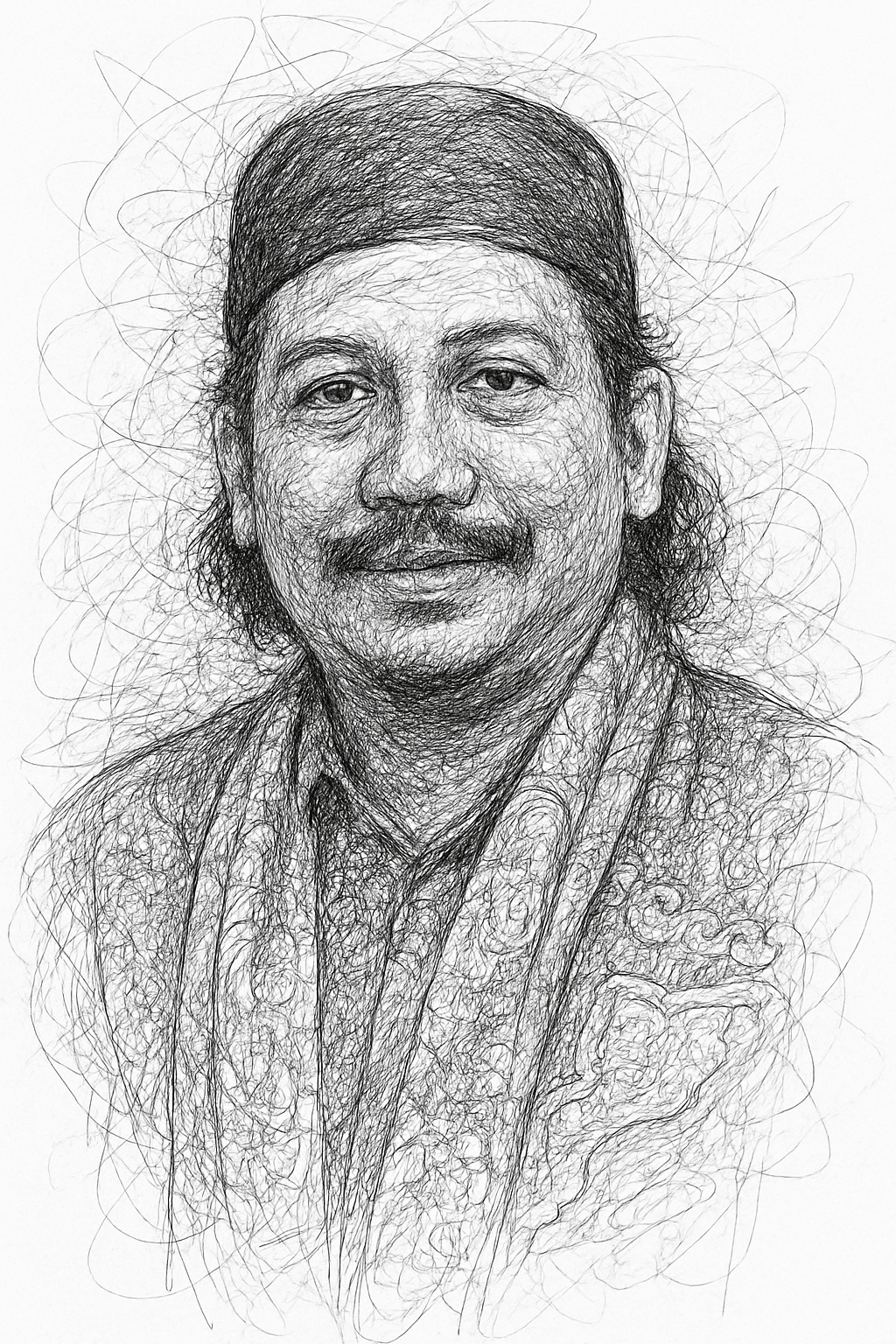Oleh: KH. Aguk Irawan MN
31 Oktober 2025, lantai dasar Gedung Filsafat UGM menjadi saksi berlangsungnya Philosophy Book Fair, sebuah upaya untuk mengingatkan kita akan pentingnya budaya baca dan tulis. Alhamdulillah, saya turut hadir di sana dan menjadi bagian dari hajatan itu bersama budayawan Taufik Razen. Kami merasakan semangat yang sama: keprihatinan atas krisis literasi yang melanda generasi kita.
Padahal para pendiri bangsa ini jelas merupakan aktivis literasi. Sebutlah Bung Karno, Bung Hatta, Tan Malaka, Syahrir, Cokroaminoto, Agus Salim, Muhammad Yamin, KH Hasyim Asy‘ari, KH Ahmad Dahlan, KH Wahid Hasyim, Ki Hajar Dewantara, dan banyak lagi. Mereka semua memiliki satu kesamaan: kecintaan pada buku dan ilmu pengetahuan.
Bung Karno, misalnya, menulis Di Bawah Bendera Revolusi, sebuah karya yang menjadi inspirasi perjuangan kemerdekaan Indonesia hingga hari ini. Bung Hatta menulis Demokrasi Kita dan sejumlah risalah tiga jilid, masing-masing sekitar 600 halaman—karya yang membahas pentingnya demokrasi dan kebebasan.
Agus Salim menulis Riwayat Kedatangan Islam di Indonesia, serta sebuah karya berbahasa Belanda yang amat terkenal, Gods Laatste Boodschap—sebuah tulisan yang menelusuri secara historis datangnya Islam di Nusantara dan pentingnya spiritualitas bagi masyarakat. Sementara Tan Malaka menulis Madilog, karya monumental yang membahas filsafat dan ilmu pengetahuan.
Namun hari ini, generasi kita nampaknya tengah mengalami krisis literasi. Banyak yang menyerahkan begitu saja “tugas” menulis kepada AI, sementara budaya baca digantikan dengan budaya menonton. Kita lebih suka membaca berita singkat di media sosial daripada membaca buku serius. Kita lebih suka menonton video ketimbang membaca artikel. Ini adalah tanda-tanda krisis literasi yang serius.
Acara Philosophy Book Fair di UGM kemarin merupakan upaya untuk mengingatkan kita kembali akan pentingnya budaya baca dan tulis. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk berefleksi, mengingat kembali warisan besar para pendiri bangsa, dan memulai lagi perjalanan literasi kita.
Dalam pembukaan sarasehannya, Taufik Razen menekankan pentingnya literasi bagi masyarakat. “Literasi adalah kunci untuk memahami dunia dan diri sendiri,” katanya. “Untuk memahami watak bangsa ini, kita bisa menelusurinya dari banyak peninggalan warisan intelektual yang ditulis dengan berbagai aksara, terutama Kawi dan Carakan,” tuturnya sambil memperlihatkan karya Zoetmulder yang berisi ribuan sinopsis kesusastraan Nusantara—nyaris tak tersentuh oleh generasi Z.
“Untuk tahu kepribadian masyarakat Nusantara, tidak bisa tidak, kita harus belajar memahami watak dan adat Kalang. Tanpa literasi itu, kita akan menjadi masyarakat Indonesia yang buta dan tuli terhadap diri sendiri,” tambahnya.
Saya sendiri merasa terharu ketika melihat masih ada antusiasme dari para mahasiswa yang hadir di acara tersebut—meskipun jumlahnya tak seberapa banyak. Mereka bertanya, berdiskusi, dan membaca buku-buku yang dipamerkan. Ini adalah tanda bahwa masih ada harapan bagi generasi kita untuk kembali mencintai literasi.
Kita perlu menghidupkan kembali budaya literasi: membaca lebih banyak buku, menulis lebih banyak artikel, dan berdiskusi lebih banyak tentang ide-ide. Kita perlu mengajak generasi muda untuk mencintai buku, mencintai ilmu pengetahuan, dan mencintai kebijaksanaan.
Di era digital ini, kita perlu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan literasi, bukan menggantinya. Gunakan media sosial untuk mempromosikan buku, ilmu pengetahuan, dan kebijaksanaan.
Mari kita mulai dari diri sendiri. Mari membaca lebih banyak, menulis lebih banyak, dan berdiskusi lebih banyak. Mari kita hidupkan kembali budaya literasi, agar Indonesia menjadi bangsa yang lebih cerdas, lebih bijak, dan lebih maju.
Wallahu a‘lam bish-shawab